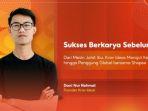Pertarungan Berbahasa di Era Medsos
Media sosial (medsos) mempengaruhi kehidupan manusia dalam banyak aspek, termasuk dalam aspek berbahasa. Bagi generasi muda, hal ini menjadi peluang
Oleh: Florianus Apung
Mahasiswa STFK Ledalero
SUATU bahasa menunjukkan kualitas peradaban dari pemilik bahasa. Kualitas itu sedikit tergerus dengan perkembangan media sosial, terutama dalam diri generasi muda. Media sosial dituding telah 'memperkosa' bahasa Indonesia.
Media sosial (medsos) mempengaruhi kehidupan manusia dalam banyak aspek, termasuk dalam aspek berbahasa. Bagi generasi muda, hal ini menjadi peluang serentak tantangan. Peluang dalam arti bahwa media sosial bisa menjadi sarana memupuk kemampuan berbahasa secara baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan berbahasa Indonesia. Sedangkan tantangan dalam arti bahwa media sosial bisa menjadi alat untuk 'memporak-porandakan' bahasa Indonesia beserta aturan-aturan yang mengikatnya.
Media sosial dengan kecanggihan yang ditawarkannya dapat menjadi sarana untuk menggali beragam informasi tentang berbahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini, untuk mengakses aturan-aturan berbahasa Indonesia sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Selain itu, media sosial dapat pula menjadi sarana untuk berdiskusi tentang perkembangan berbahasa dengan para pakar bahasa yang tidak bisa ditemui secara langsung. Sebagai misal, jika dosen bahasa dan sastra Indonesia di ruangan kelas mengalami kebuntuan dalam menjelaskan perkembangan bahasa terbaru seperti fenomena bahasa gaul, seorang mahasiswa -barangkali dengan ketidakpuasan di ruangan kelas -dapat menggali akurasi informasi berbahasa dalam media sosial sekaligus membuat perbandingan dari status/tweet atau tulisan orang lain. Potensi inilah yang sebenarnya bisa dilirik.
Namun demikian, media sosial mempunyai daya destruktif terhadap bahasa. Status, tweet, dan tulisan lain di media sosial acapkali rancu. Keadaan ini bisa mempengaruhi cara berbahasa kaum muda yang notebene sedang menempuh pendidikan dalam jenjang perguruan tinggi. Keluhan-keluhan yang acapkali muncul dari para dosen perguruan tinggi adalah rancunya penggunaan bahasa tulisan dari hampir semua mahasiswa. Beberapa diantaranya mencoba memetakan persoalan yang ada dan mengambil kesimpulan bahwa generasi muda zaman ini memiliki kecenderungan umum untuk mentransfer bahasa percakapan/lisan ke dalam tulisan. Sebagai misal, orang bisa menulis demikian: Politik uang 'membikin' pilkada menjadi tidak demokratis. Kata bikin dalam kalimat ini memang bisa dimengerti, akan tetapi tidak bisa dibenarkan dari struktur berbahasa. Bikin adalah bahasa percakapan dan menjadi tidak benar ketika dikonstruksi menjadi kata kerja membikin. Seharusnya menjadi: politik uang membuat pilkada menjadi tidak demokratis.
Apakah kita harus mengubah paradigma?
Memetakan persoalan berbahasa dalam diri kaum muda sekaligus mencari solusinya bukanlah perkara kelas ringan. Pertama, media sosial akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Media sosial adalah sarana komunikasi yang sudah terberi dan sulit dibendung. Perkembangan ini dapat memicu perkembangan dalam berbahasa, dalam struktur dan rasa bahasa. Ada kecemasan futuristik bahwa bahasa dalam media sosial akan mengambil alih tahta aturan-aturan berbahasa yang baik dan benar. Bahasa media sosial dilihat sebagai sesuatu yang wajar, dan selanjutnya diterima sebagai kebenaran umum. Kedua, daya rusak media sosial adalah karena kebebasannya dalam menggunakan bahasa Indonesia. Tulisan-tulisan di media sosial lebih mudah dibuat dibandingkan dengan membentuk tulisan dengan terpaku pada aturan-aturan berbahasa. Fenomena ini ditemukan dalam diri kaum muda. Skripsi, paper, dan tulisan-tulisan lainnya semakin menyerupai rangkaian status yang tidak terhubung satu sama lain.
Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita perlu mengamini bahasa media sosial sebagai bahasa yang baik dan benar? Apakah kita perlu melihatnya sebagai sesuatu yang sudah terberi dan sudah saatnya diterima sebagai bagian yang mendarah daging dalam diri generasi muda? Diskusi tentang tema ini sebenarnya hendak menonjolkan dua golongan atau paradigma yang terlahir dalam waktu yang berbeda? Pertama, golongan muda yang notabene terlahir dengan gen bahasa media sosial. Golongan inilah yang memiliki kecenderungan kuat memindahkan bahasa medsos ke dalam bahasa tulisan. Kedua, golongan terdahulu yang dilahirkan dalam alam bahasa dengan perkembangan teknologi yang belum terlalu maju. Golongan inilah yang menjadi ujung tombak mempertahankan tata cara berbahasa Indonesia. Jadi persoalannya kini adalah pertarungan paradgima.
Saya tidak melihat perkembangan dan paradigma bahasa dalam generasi muda sekarang sebagai sesuatu yang mutlak salah. Demikian pun, tradisi berbahasa yang dibela generasi terdahulu tidak semestinya dilihat sebagai patokan kebenaran absolut. Maka yang diperlukan di sini adalah dialog bahasa lintas generasi. Ruang kreatif bahasa, dimana generasi muda dan generasi terdahulu bisa bertemu dan berdiskusi tentang tetek-bengek bahasa harus tercipta sehingga bisa melahirkan solusi yang bisa menyelamatkan bahasa. Selanjutnya tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga menciptakan bahasa yang nyaman, komunikatif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan berbahasa yang juga telah disepakati bersama.*